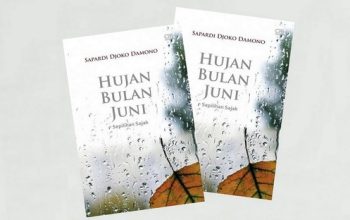BANYUMASMEDIA.COM – Sekali waktu, sebuah angka membuat saya tercekat: 749,6 juta kilogram buah. Bukan hasil panen dari ladang-ladang Nusantara, bukan kiriman dari kebun-kebun rakyat di lereng Merapi, bukan juga persembahan musim dari pegunungan Malino. Itu adalah volume buah yang kita impor sepanjang tahun 2022. Nilainya mendekati Rp30 triliun.
Ya, tiga puluh triliun. Bukan untuk alat berat, bukan untuk teknologi tinggi, bukan pula untuk senjata atau infrastruktur. Hanya untuk buah. Luar biasa—dalam makna yang lebih dekat ke “ganjil” daripada “mengagumkan.”
Indonesia, negeri yang pernah dengan bangga menamakan dirinya agraris, hari ini menjadi pasar empuk buah impor. Di pasar swalayan kita jumpai jeruk dari Mandarin, apel dari Washington, pir dari Tiongkok, kiwi dari Selandia Baru, kurma dari Tunisia, bahkan durian dari Thailand. Lengkeng dan leci, buah tropis yang seharusnya mudah tumbuh di sini, kini datang dari Vietnam.
Data dari Badan Pusat Statistik mengabarkan: Tiongkok adalah penyumbang terbesar buah-buahan impor ke Indonesia, disusul oleh Thailand, Amerika Serikat, Mesir, dan Vietnam. Negara-negara yang, ironisnya, beberapa di antaranya memiliki iklim serupa dengan kita. Maka, pertanyaan pun menyeruak: di mana para petani kita? Di mana kebun-kebun buah yang dulu menjadi sumber kehidupan pedesaan?
Masalah ini tak bisa dijawab sekadar dengan nostalgia tentang masa lalu ketika buah mangga dari Indramayu melimpah atau ketika jeruk keprok dari Garut diburu menjelang Imlek. Sebab nostalgia adalah ingatan yang sering kali menolak kenyataan hari ini.
Kita harus mengakui: ada yang keliru dalam cara kita mengelola tanah kita sendiri. Bukan karena lahan tak ada. Bukan karena matahari dan hujan tak ramah. Tetapi mungkin karena kita terlalu percaya pada “efisiensi” pasar global, dan terlalu alpa pada ketahanan pangan lokal.
Ekonomi kita terlampau tunduk pada logika dagang jangka pendek. Apel dari luar bisa dijual lebih murah—atau lebih konsisten bentuk dan ukurannya—dibanding apel dari Batu. Lengkeng dari Vietnam lebih stabil pasokannya ketimbang dari Wonosobo. Buah naga dari Thailand tampil lebih menggiurkan di rak-rak swalayan.
Di sisi lain, kita melihat ironi ini tumbuh: desa-desa yang dulu menghasilkan buah, kini menjelma menjadi ladang beton, tempat vila-vila bertebaran. Petani beralih menjadi buruh harian atau pengantar makanan. Anak-anak muda tak lagi mengenal musim panen, kecuali lewat meme atau film dokumenter.
Tentu saja impor bukan dosa. Tidak semua bisa kita tanam sendiri. Tapi ketika buah-buahan tropis pun harus kita datangkan dari luar, pertanyaan besarnya bukan sekadar soal perdagangan. Ini tentang siapa yang kita beri makan dengan uang kita: petani di negeri sendiri, atau industri agrikultur asing?
Mungkin yang paling menyesakkan bukanlah angka triliun itu, tapi kesadaran bahwa kita, pelan-pelan, telah melupakan buah yang kita tanam sendiri. Kita tidak hanya kehilangan hasilnya, tapi juga kehilangan budaya bercocok tanamnya, kehilangan rasa lokalnya, kehilangan relasi antara manusia dan tanahnya. Di tengah banjir buah impor, kita seperti bangsa yang memakan bayangannya sendiri: kenyang, tapi hampa.
Kita hidup di negeri yang barangkali terlalu mudah mengimpor, dan terlalu lambat bertanya: apa yang sedang kita tanam? Dalam setiap irisan apel Fuji dan setiap gigitan pir Tiongkok, ada pertanyaan yang menggantung: apa kabar kebun kita sendiri?
Barangkali sudah waktunya kita berhenti terpukau oleh keseragaman buah dalam plastik dan mulai menengok kembali keberagaman rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Sebab bangsa yang menggantungkan selera pada negeri lain, pelan-pelan juga kehilangan keberanian untuk merasakan dirinya sendiri.[]
Sumber tulisan: www.salamyogyakarta.com