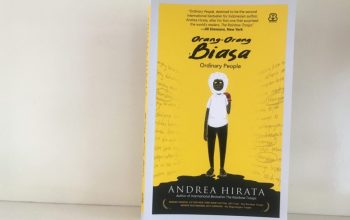BANYUMASMEDIA.COM – Di tengah hiruk-pikuk perbincangan tentang masa depan bangsa, sering kali kita lupa bahwa fondasi peradaban tidak dibangun di gedung parlemen, bukan pula di ruang rapat korporasi, melainkan di ruang-ruang kecil bernama rumah. Di sanalah nilai-nilai dasar manusia ditempa: kasih, tanggung jawab, disiplin, dan cinta. Dan di tengah ruang itulah, berdiri sosok yang sering terabaikan dalam wacana publik, seorang ayah.
Ayah bukan sekadar pencari nafkah atau pelengkap struktur keluarga. Ia adalah penjaga nilai, pengarah arah, dan pilar tegaknya peradaban. Ketika seorang ayah memahami perannya, sesungguhnya ia tengah membangun fondasi kokoh bagi masyarakat yang beradab. Sebaliknya, ketika peran ayah menghilang, maka peradaban pun kehilangan orientasinya.
Islam, sebagai agama yang menata kehidupan manusia secara menyeluruh, telah menempatkan hubungan keluarga dalam tatanan yang sangat filosofis. Dalam hal ini, menarik untuk menelaah kembali hierarki sederhana sebuah “kekuasaan” dalam keluarga sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW.
Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, “Siapakah yang harus aku hormati?”
Rasul menjawab, “Ibumu.”
Sahabat itu bertanya lagi, “Lalu siapa lagi?”
Rasul menjawab, “Ibumu.”
Masih penasaran, sahabat itu bertanya kembali, “Lalu siapa lagi?”
Sekali lagi Rasul menjawab, “Ibumu.”
Barulah setelah ditanya keempat kalinya, Rasul bersabda, “Ayahmu.”
Sebuah percakapan yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Islam membangun tatanan keluarga dengan menempatkan ibu sebagai pusat kasih, sumber kehidupan, dan fondasi moral yang harus dihormati tiga kali lipat dibanding ayah. Ini adalah cara Islam menegakkan keseimbangan dan menguatkan posisi perempuan dalam peradaban. Jika di banyak budaya perempuan dianggap lemah, maka Islam justru memuliakannya, bukan dengan retorika, tetapi dengan menegaskan kewajiban anak untuk menghormati ibunya terlebih dahulu.
Namun, Islam juga menempatkan laki-laki pada posisi yang tak kalah penting. Ketika perempuan dan laki-laki disatukan dalam ikatan suami istri, Islam kembali menegaskan sebuah struktur yang harmonis dan hierarkis. Seorang istri diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada suaminya dalam koridor ketaatan kepada Allah Ta’ala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya manusia diperbolehkan bersujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.”
Ungkapan ini bukan legitimasi untuk menindas, melainkan simbol tanggung jawab besar yang dipikul seorang suami. Ia memang pemimpin, namun kepemimpinannya terikat oleh standar ketaatan kepada Allah SWT. Dan di balik “super power”-nya seorang suami di hadapan istrinya, tetap ada kenyataan yang tak dapat dihapus: betapapun gagahnya ia, sang suami tetaplah milik ibunya. Ia pun tunduk dalam kasih dan restu seorang perempuan yang melahirkannya.
Hierarki nilai inilah yang menjadi dasar kuat bagi terbentuknya masyarakat yang beradab. Ketika seorang ayah memahami posisinya, sebagai anak yang berbakti, suami yang bijak, dan pemimpin yang adil, maka ia sedang memantulkan cahaya peradaban dari dalam rumahnya sendiri.
Sebaliknya, ketika nilai itu hilang, yang muncul adalah krisis sosial yang kita saksikan hari ini: anak yang durhaka, istri yang kehilangan arah, suami yang semena-mena, dan orang tua yang dilupakan di usia senja.
Padahal, akar dari semua itu bukan semata ekonomi, melainkan kegagalan menanamkan kesadaran hierarkis dalam keluarga. Hierarki bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau rendah, melainkan tentang penempatan peran yang proporsional, disertai tanggung jawab yang seimbang. Ibu menjadi sumber kasih, ayah menjadi penegak nilai, dan anak menjadi penerus amal kebaikan. Ketika keseimbangan itu terjaga, maka keluarga akan menjadi miniatur peradaban yang utuh.
Di era modern, peran ayah sering kali direduksi menjadi sekadar “penopang finansial”. Padahal, kontribusi terbesarnya bukan pada materi, melainkan pada keteladanan. Anak belajar integritas bukan dari ceramah, tetapi dari bagaimana ayahnya bersikap di rumah. Anak mengenal tanggung jawab bukan dari buku pelajaran, tetapi dari bagaimana ayah menepati janji. Ayah adalah simbol arah. Ia bukan sekadar kepala keluarga, tetapi kompas yang menuntun langkah anak-anak menuju kehidupan yang bermartabat.
Membangun peradaban tidak bisa dilakukan hanya dengan program sosial atau kebijakan negara. Ia dimulai dari ruang keluarga yang kecil, dari meja makan yang hangat, dari percakapan sederhana antara ayah dan anak tentang nilai, tentang iman, tentang arti menjadi manusia yang baik. Di sanalah titik awal peradaban dibentuk.
Sebuah refleksi perlu kita renungkan: bagaimana kita memposisikan diri dalam struktur yang diajarkan Isla, sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, atau sebagai ibu. Ketika kesadaran ini tumbuh dan dipahami sebagai sistem yang saling menopang, maka insya Allah berbagai persoalan sosial akan berkurang dengan sendirinya. Tak akan ada lagi lansia yang ditelantarkan anak-anaknya, tak ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, tak ada istri yang menentang suami, dan tak ada suami yang berlaku semena-mena terhadap istri.
Membangun kefahaman memang bukan perkara mudah. Ia adalah jalan panjang yang tak bisa ditempuh sendirian. Namun jika setiap ayah mau memulai dari rumahnya sendiri, mendidik dengan cinta, menuntun dengan teladan, dan menegakkan nilai dengan iman, maka sesungguhnya ia sedang menanam benih peradaban yang akan tumbuh melampaui zamannya.
Dan kelak, ketika sejarah mencatat peradaban besar lahir dari keluarga yang kokoh, barangkali nama seorang ayah tak disebut. Tapi jejaknya akan tetap ada, di hati anak-anaknya, di keteguhan keluarganya, dan di nilai-nilai yang ia wariskan dengan cinta dan kesadaran.
Penulis: Dedi Supriyanto (Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Banyumas)