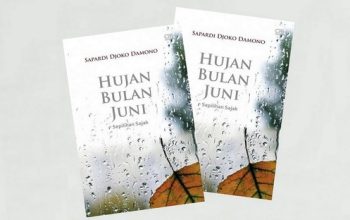BANYUMASMEDIA.COM – Ahmad Tohari, sebuah nama yang mungkin tidak asing lagi bagi orang Banyumas. Lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, pada 13 Juni 1948, Ahmad Tohari tak hanya dikenal sebagai sastrawan, tapi juga budayawan yang begitu piawai menulis tentang desa, tentang alam, tentang wong cilik, tentang orang-orang yang kadang kita temui, tapi sering kita abaikan.
Saya masih ingat betul, sekitar tahun 2013. Waktu itu saya baru saja menginjak semester awal perkuliahan, dan ada tugas wajib: membaca dan meresensi buku sastra. Sebagai mahasiswa yang realistis (baca: malas ribet), saya mulai berburu buku dengan satu kriteria: halaman yang tidak terlalu tebal. Maka saya masuk Gramedia dengan misi itu. Sampai akhirnya mata saya tertuju pada sebuah buku mungil dengan sampul putih bersih, bertuliskan judul besar Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Tebalnya? 71 halaman. Wah, ini dia, batin saya waktu itu.
Awalnya saya tidak terlalu peduli siapa penulisnya. Yang saya tahu, tugas saya akan selesai dengan membaca buku itu. Tapi saya keliru. Buku itu justru meninggalkan jejak yang panjang di kepala saya.
Judulnya, Senyum Karyamin, terdengar cerah. Saya pikir, ini akan menjadi kisah ringan tentang tawa, tentang bahagia. Namun, saat mulai membaca, saya justru disambut oleh kisah tentang Karyamin, seorang pencari batu kali yang harus bolak-balik memikul beban berat di pundaknya, dengan tubuh lelah, perut kosong, dan utang yang menumpuk. Seorang wong cilik yang bahkan untuk menertawakan hidupnya sendiri, harus mengumpulkan tenaga.
Saya sempat bingung: kenapa judulnya justru Senyum Karyamin? Bukankah yang saya temukan adalah kisah getir? Bukankah sepanjang cerita, Karyamin lebih sering jatuh dan tergelincir, baik secara harfiah maupun dalam hidupnya? Tapi justru di sanalah letak ironi yang begitu halus dalam cerita ini. Ahmad Tohari memberi kita pelajaran: senyum wong cilik itu bukan senyum bahagia, tapi senyum perlawanan. Senyum yang jadi tameng terakhir ketika hidup sudah terlalu pahit.
Karyamin tersenyum bukan karena ia senang, tapi karena kalau ia tak tersenyum, mungkin ia akan benar-benar tumbang.
Yang membuat cerpen ini makin membekas adalah cara Ahmad Tohari melukis desa dan alam sekitarnya. Sungai yang mengalir, batu-batu yang licin, burung paruh udang yang berkali-kali lewat, daun jati yang melayang menentang arus, semuanya bukan sekadar tempelan. Ahmad Tohari membuat kita seolah ikut melangkah bersama Karyamin, ikut mendengar suara air, ikut mencium aroma basah tanah, ikut merasa beratnya beban di pundak. Ahmad Tohari tidak hanya menulis latar, ia menulis napas.
Dan ini yang jarang dilakukan sastrawan lain. Ahmad Tohari tidak meletakkan alam desa sebagai latar mati. Alam dalam cerpennya adalah bagian yang hidup, yang mengalir bersama cerita. Alam tidak hanya menemani, tapi juga mempengaruhi perasaan tokohnya. Seperti burung paruh udang yang mula-mula membuat Karyamin jatuh, tapi di akhir cerita justru ia maafkan. Burung itu, seperti Karyamin, sedang berjuang. Dan Karyamin menyadari itu.
Membaca ulang Senyum Karyamin hari ini, saya seperti diingatkan kembali pada potret wong cilik yang sering kita temui di sekitar kita. Orang-orang yang tetap tersenyum meski tahu esok masih suram. Orang-orang yang kadang jadi bahan lelucon sistem, yang ditagih sumbangan kemanusiaan, padahal dirinya sendiri nyaris tak bisa makan. Bahwa di balik senyum tipis seperti Karyamin, ada ketabahan yang mungkin tak bisa kita bayangkan.
Barangkali itu mengapa cerpen ini masih relevan sampai sekarang. Wong cilik seperti Karyamin masih banyak. Mereka masih ada di sungai, di pasar, di jalan-jalan. Mereka masih memikul beban yang tak ringan, dan seringkali, mereka masih tetap memilih tersenyum. [asr]